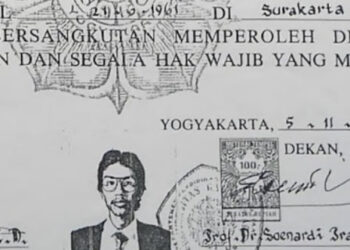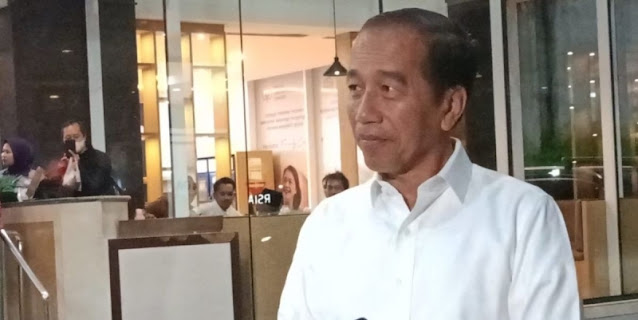Penulis: Arjuna Syahputra**
POLEMIK terkait penetapan empat pulau di Aceh Singkil sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 merupakan peristiwa serius yang menyentuh integritas wilayah dan kedaulatan administratif Provinsi Aceh.
Keputusan ini menetapkan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek sebagai milik Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan bukan lagi bagian dari Provinsi Aceh. Penetapan tersebut mengundang gelombang penolakan, terutama dari masyarakat Aceh Singkil yang merasa bahwa pulau-pulau tersebut telah menjadi bagian dari ruang hidup dan warisan sejarah mereka sejak lama.
Sikap penolakan yang disampaikan oleh masyarakat lokal bukan semata karena dorongan emosional atau sentimen kedaerahan sempit, melainkan dilandasi oleh argumen yang kuat dari berbagai aspek: historis, yuridis, dan sosiologis.
Ketiganya membentuk fondasi logis dan rasional bahwa keputusan Kemendagri tersebut merupakan bentuk kekeliruan administratif yang memiliki dampak serius terhadap keutuhan wilayah Aceh, serta dapat menciptakan preseden buruk bagi persoalan batas wilayah antarprovinsi di masa depan.
Secara historis, keempat pulau tersebut telah sejak lama menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Masyarakat lokal mengenal wilayah ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas daerah mereka.
Dalam catatan sejarah administratif Indonesia, khususnya dalam Peta Republik Indonesia Tahun 1956 yang dijadikan rujukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), disebutkan secara tegas bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada peta tersebut.
Ini berarti bahwa keberadaan keempat pulau tersebut di dalam wilayah administrasi Aceh memiliki landasan hukum yang sah dan telah diakui negara sejak lama.
Pasal 1 ayat (2) UUPA secara eksplisit menyebutkan bahwa batas wilayah Aceh adalah batas wilayah sebagaimana dimuat dalam Peta Republik Indonesia Tahun 1956. Dengan begitu, keberadaan keempat pulau tersebut dalam wilayah Aceh tidak hanya memiliki basis historis, melainkan juga didukung oleh payung hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pascareformasi dan pasca konflik.
Secara yuridis, keputusan Kemendagri tersebut bertentangan langsung dengan UU yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam prinsip hukum tata negara, ketika terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori).
Artinya, jika keputusan menteri bertentangan dengan undang-undang, maka keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dibatalkan.
Di sinilah letak urgensi Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas dan tidak hanya bergantung pada pendekatan persuasif melalui dialog. Meskipun pendekatan diplomasi dan komunikasi antar pemerintah tetap penting, namun langkah litigasi atau jalur hukum adalah satu-satunya cara yang memiliki kekuatan memaksa terhadap pihak yang menerbitkan keputusan yang dinilai cacat hukum.
Dalam konteks hukum administrasi negara, terdapat asas yang dikenal sebagai contrarius actus, yakni bahwa pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang menerbitkan suatu keputusan juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri adalah pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan keputusannya sendiri.
Namun demikian, jika Kemendagri tidak menunjukkan kehendak untuk meninjau ulang atau membatalkan keputusannya, maka jalan yang paling rasional dan sah secara hukum adalah menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Upaya ini bukan hanya legal, tetapi juga strategis karena akan menempatkan persoalan ini dalam forum peradilan yang independen dan memiliki otoritas untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan hukum.
Melalui PTUN, Pemerintah Aceh dapat menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti otentik yang mendukung klaim terhadap kepemilikan empat pulau tersebut. Bukti tersebut dapat berupa peta resmi pemerintah tahun 1956, dokumen administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, pengakuan sosial-budaya dari masyarakat setempat, dan berbagai arsip sejarah yang menunjukkan hubungan erat antara pulau-pulau tersebut dengan Provinsi Aceh.
Kekuatan argumen ini sangat penting karena dalam sengketa tata usaha negara, pembuktian administratif, yuridis, dan fakta lapangan menjadi kunci utama untuk meraih kemenangan hukum.
Lebih lanjut, jika gugatan ke PTUN berhasil dan keputusan Kemendagri dibatalkan oleh pengadilan, maka secara otomatis Kemendagri wajib mencabut keputusan tersebut. Hal ini sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur, yang berarti “putusan pengadilan harus dianggap benar”.
Artinya, setelah pengadilan memutuskan, semua pihak terkait, termasuk Kemendagri, tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi keputusan tersebut.
Langkah menggugat ke PTUN memang bukan jalan yang mudah. Diperlukan ketelitian, strategi hukum yang matang, serta kesabaran karena proses hukum bisa memakan waktu yang tidak singkat. Namun, jalan hukum ini adalah ekspresi dari niat baik dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menjaga integritas wilayahnya.
Ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Aceh bukan provinsi yang bisa dengan mudah diabaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat pusat, terutama yang menyangkut wilayah dan martabat daerah.
Jika Pemerintah Aceh bersikap pasif atau hanya mengandalkan pendekatan non-litigasi, maka dikhawatirkan keputusan ini akan menjadi preseden yang membahayakan di masa depan.
Akan terbuka ruang bagi pengabaian batas wilayah yang sah oleh pemerintah pusat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik horizontal antar warga, gangguan stabilitas keamanan, serta mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Kepedulian masyarakat Aceh Singkil terhadap masalah ini sangat patut diapresiasi. Mereka tidak tinggal diam atas perampasan wilayah mereka yang dilakukan secara administratif oleh pusat. Penolakan keras dari masyarakat adalah wujud partisipasi aktif dan rasa memiliki yang kuat terhadap tanah kelahiran mereka.
Dalam konteks otonomi daerah dan semangat reformasi, partisipasi seperti ini semestinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat, bukan justru diabaikan.
Pemerintah Aceh harus menjadikan momentum ini sebagai upaya konsolidasi internal untuk memperkuat posisi hukum dan politiknya di tingkat nasional.
Di samping mengajukan gugatan hukum, Pemerintah Aceh juga dapat memperluas jaringan advokasi dengan melibatkan para akademisi, pakar hukum tata negara, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh nasional untuk memperjuangkan keadilan atas penetapan batas wilayah ini.
Pendekatan komprehensif yang menggabungkan litigasi dan non-litigasi akan memperkuat posisi Aceh dalam sengketa ini.
Jika Pemerintah Aceh berhasil memenangkan gugatan dan membatalkan keputusan Kemendagri tersebut, maka itu tidak hanya akan menjadi kemenangan simbolik, tetapi juga kemenangan strategis yang akan mempertegas posisi Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ini sekaligus akan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat bahwa segala bentuk keputusan administratif yang menyangkut wilayah suatu daerah harus didasarkan pada hukum dan data sejarah yang kuat, bukan sekadar kepentingan politik atau administratif sesaat.
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh tentu menghormati tatanan hukum dan pemerintahan yang berlaku. Namun, penghormatan tersebut harus bersifat timbal balik.
Pemerintah pusat pun wajib menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Kekhususan ini tidak hanya terletak pada aspek syariat Islam dan otonomi fiskal, tetapi juga pada integritas wilayah yang telah ditetapkan secara sah dalam peraturan perundang-undangan.
Pada akhirnya, masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Singkil, menaruh harapan besar kepada Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah konkret dan maksimal dalam memperjuangkan keempat pulau tersebut agar kembali secara de jure menjadi bagian dari wilayah Aceh.
Harapan ini tidak berlebihan, karena menyangkut harga diri, warisan sejarah, dan identitas yang telah tertanam lama dalam sanubari rakyatnya.
Kesimpulannya, polemik empat pulau Aceh Singkil harus disikapi secara serius dan profesional oleh Pemerintah Aceh. Tidak cukup dengan dialog dan lobi, tetapi harus dilengkapi dengan langkah hukum yang sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dengan dasar historis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, peluang untuk memenangkan gugatan ini sangat terbuka. Pemerintah Aceh harus membuktikan kepada rakyatnya bahwa mereka memiliki komitmen penuh dalam menjaga integritas wilayah dan martabat daerah.
Ini bukan sekadar pertarungan administratif, melainkan pertarungan eksistensial untuk mempertahankan kehormatan dan masa depan Aceh di tengah dinamika kebijakan nasional yang kadang tak berpihak.
**). Penulis adalah Koordinator Bidang POLHUKAM BEM FH USK