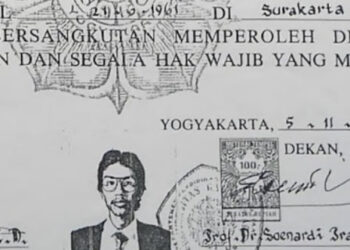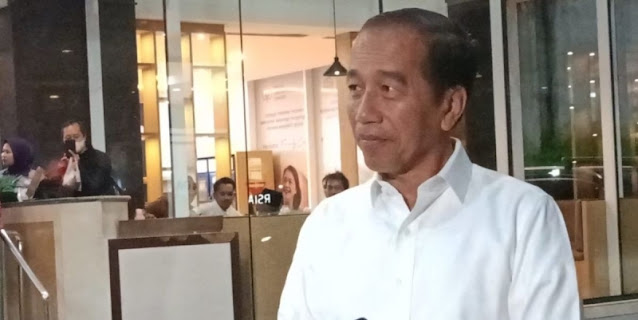Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025, menjelang HUT ke-80 RI, di hadapan Dewan Terhormat DPR/DPD RI, bisa dibilang spektakuler, garang, tegas, dan tentu saja memukau para wakil rakyat. Standing applause membahana, seolah mengatakan, “Ini baru pidato!” Sementara di luar gedung, sebagian publik mungkin tersenyum tipis, menyadari bahwa pidato yang berapi-api itu tidak otomatis membuat kantong mereka lebih tebal.
Seperti biasa, respons publik terbagi ada yang memuji luar biasa—bahkan sampai lupa napas—dan ada yang mengejek, menuding semua pujian hanyalah “omon-omon” belaka. Tapi di tengah gegap gempita, salah satu topik paling relevan dan menarik dicermati [fiskal] yakni kebijakan yang secara langsung memengaruhi kantong rakyat dan kemampuan negara membiayai diri sendiri.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo membeberkan APBN 2026. Belanja negara Rp 3.786,5 triliun, pendapatan Rp 3.147,7 triliun, defisit Rp 638,8 triliun (2,48% PDB). Semua ini demi mendukung delapan agenda prioritas nasional—mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan semesta. Sebuah rangkaian tujuan mulia yang terdengar hebat, meski tetap harus diingat bahwa rakyat yang membayar pajak belum tentu merasakan dampak langsung dari semua janji itu.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang akan menanggung semuanya? Jawabannya: rakyat melalui pajak. Pajak memang menjadi tulang punggung APBN, sementara pendapatan lain seperti dividen BUMN, penjualan aset, atau hibah terdengar lebih seperti bonus yang menyenangkan di atas kertas.
Pemerintah pun menetapkan target tax ratio naik menjadi 10,54% dari PDB, demi “memperkuat kapasitas fiskal negara.” Artinya, pemerintah berharap lebih banyak dari rakyat tanpa menambah jenis pajak baru—sebuah trik manis yang terdengar logis di pidato, tapi tetap menuntut warga untuk patuh, rajin membayar, dan tentu saja… tersenyum sambil merogoh kantong.
Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai eksekutor menegaskan penerimaan pajak dipatok Rp 2.357,7 triliun, ditambah kepabeanan dan cukai Rp 334,3 triliun, agar APBN cukup untuk membiayai pembangunan strategis. Reformasi administrasi pajak, digitalisasi, dan penegakan hukum jadi “senjata rahasia” untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan kata lain: teknologi memantau transaksi rakyat lebih efektif daripada pidato di DPR yang berapi-api.
Di sisi lain, utang negara tetap menjadi bayang-bayang. Sebagian penerimaan negara harus dipakai untuk membayar bunga dan cicilan pokok, sehingga kapasitas belanja untuk kebutuhan rakyat terbatas. Rasio utang diperkirakan 31–33% dari PDB pada 2025–2026. Tidak apa-apa, kata pemerintah—lumrah dilakukan—meski kenyataannya rakyat bisa menebak mana prioritas, pembangunan atau bunga utang?
Sebagai penutup mari kita renungkan ungkapan Thomas Jefferson (1791) – Pemikiran tentang Pajak dan Kesejahteraan Umum. Dalam “Opinion on the Constitutionality of a National Bank” (1791), Jefferson menekankan bahwa: “Pajak seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan segelintir orang.”
Akhirnya, semua strategi terdengar elegan. Meningkatkan tax ratio, reformasi perpajakan, efisiensi belanja, dan pengelolaan BUMN. APBN harus tetap sehat, defisit terkendali. Tapi di balik pidato megah dan standing applause, rakyat hanya bisa bertanya ketika pajak dinaikkan, reformasi digalakkan, dan utang tetap ada, apakah kehidupan mereka benar-benar ikut meningkat? Atau mereka hanya jadi subjek pidato spektakuler yang menggetarkan hati DPR, tapi kantong tetap menipis?