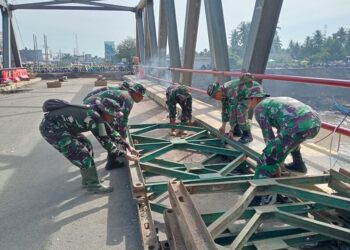AKSI penyerobotan atau yang kini akrab disebut sebagai “begal pulau” terhadap empat pulau yang selama ini secara historis dan administratif berada di wilayah Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, telah menjadi sorotan nasional. Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara bukan hanya menciptakan ketegangan administratif, tetapi juga luka kolektif bagi masyarakat Aceh.
Polemik ini mencuat tidak hanya karena menyangkut urusan batas wilayah, melainkan karena dugaan kuat adanya konflik kepentingan yang menyelimuti kebijakan tersebut. Dari pejabat pusat hingga tokoh lokal, semuanya ikut terseret dalam perdebatan ini, yang kian menajam dan menguak aroma busuk dari campur tangan kepentingan politik dan ekonomi.
Konflik Bukan Sekadar Tapal Batas
Banyak pihak mencoba mengkonstruksi narasi bahwa permasalahan ini merupakan sengketa lama yang baru mendapat perhatian serius. Basarin Yunus Tanjung dari Pemerintah Provinsi Sumut, serta Safrizal ZA dari Kemendagri menyampaikan bahwa masalah perbatasan ini sudah mengendap selama puluhan tahun. Namun, pernyataan ini terbantahkan oleh data historis yang kuat. Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI, tegas menyatakan bahwa keempat pulau tersebut memang bagian dari Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956.
Surat resmi Hindia Belanda bertanggal 8 Juli 1925 yang dikeluarkan di Kutaradja dan ditujukan ke Weltevreden, Jakarta, turut memperkuat klaim ini. Laporan itu mencatat wilayah administrasi Singkil, termasuk pulau-pulaunya, tanpa mencantumkan adanya sengketa dengan wilayah Tapanuli (Sumut saat ini). Artinya, tidak ada dasar historis yang sahih bagi Sumut untuk mengklaim keempat pulau tersebut.
Namun sayangnya, pendekatan yang diambil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru mengarah pada kebijakan yang tidak hanya maladministratif, namun juga memanipulasi narasi sejarah. Penjelasannya tentang adanya perdebatan antara Residen Aceh dan Residen Tapanuli pada 1928 sangat problematik, karena pada tahun tersebut Aceh masih berada dalam masa konflik dan di bawah kendali militer, bukan sipil. Maka sangat disayangkan jika seseorang dengan latar belakang akademik setinggi Tito mengabaikan fakta-fakta dasar tersebut.
Kepentingan di Balik Kebijakan
Ada pertanyaan besar yang perlu diajukan: mengapa pemerintah pusat begitu ngotot mengambil alih administrasi keempat pulau tersebut? Jawabannya bisa jadi terletak pada potensi kekayaan alam dan prospek investasi masa depan. Muslim Ayub, anggota DPR, menyebutkan bahwa terdapat potensi migas besar di kawasan tersebut, dan bahwa Uni Emirat Arab sudah sejak empat tahun lalu berminat untuk berinvestasi di Aceh Singkil.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan mantan pejabat tinggi Muhammad Said Didu yang mencuitkan bahwa “Geng Solo sedang bekerja,” menunjukkan adanya dugaan bahwa keputusan ini merupakan bentuk loyalitas kepada keluarga Jokowi, terutama menantunya Bobby Nasution, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumut. Bobby bahkan berusaha “berkompromi” dengan Mualem di Aceh untuk pengelolaan bersama, meskipun upayanya ditolak secara halus.
Jerry Massie dari P3S bahkan menyebutkan bahwa tindakan ini berpotensi memicu konflik horizontal karena sangat sarat muatan politis. Menurutnya, bukan hanya migas, tetapi juga nikel, batu bara, dan emas menjadi latar belakang pengalihan wilayah ini. Maka tidak berlebihan jika publik mencium aroma busuk dari skenario ini.
Konflik Kepentingan: Wajah Buram Demokrasi Kapitalistik
Konflik kepentingan menjadi akar dari banyak kebijakan publik yang menyimpang. Di sinilah persoalan etika publik dan integritas pejabat diuji. Ketika seorang pejabat memiliki konflik kepentingan, maka keputusan yang diambil tidak lagi mewakili kepentingan publik, tetapi menjadi alat akumulasi kekuasaan dan kekayaan kelompok tertentu.
Dalam kasus ini, kita melihat bagaimana Kepmendagri digunakan untuk menabrak UU yang sudah lama berlaku. Di sini, logika politik dagang sapi—di mana jabatan, kebijakan, dan wilayah bisa dinegosiasikan demi kepentingan bisnis atau loyalitas politik—bermain secara terang-terangan.
Sayangnya, semua ini dilakukan dengan dalih administratif, padahal motif sebenarnya adalah politis dan ekonomis. Conflict of interest yang begitu vulgar ini mencoreng marwah pemerintahan dan semakin menegaskan bahwa demokrasi yang kita jalankan saat ini adalah demokrasi yang cacat secara struktural dan substansial.
Sudut Pandang Islam: Negara Amanah dan Kepemimpinan Tanpa Bisnis
Islam memiliki pandangan yang sangat tegas dalam hal integritas pejabat publik. Negara dalam sistem Islam tidak boleh dijalankan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Dalam sejarah, Umar bin Khattab melarang keras pejabatnya untuk berdagang, sebagaimana yang tertuang dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari.
Ketika Umar mengetahui bahwa Abu Hurairah, wali Bahrain, berdagang di luar tugasnya, maka ia segera dipanggil dan ditegur keras. Umar menyatakan, “Bisnis amir adalah kerugian.” Sebab, pejabat dalam sistem Islam dibayar (ta’widh) bukan untuk mencari tambahan, tapi untuk fokus mengurusi urusan rakyat.
Prinsip ini juga menekankan pentingnya pemisahan antara tugas sebagai penguasa dengan kepentingan ekonomi pribadi. Khalifah, Mu’awin, Wali, Amil dan para pejabat negara lainnya dilarang keras terlibat dalam aktivitas bisnis karena waktu dan wewenangnya adalah milik rakyat. Jika dilanggar, maka hukumannya bisa berupa pencopotan hingga pengembalian hak publik yang telah diambil secara tidak sah.
Bandingkan dengan sistem kapitalistik demokrasi saat ini. Kita menyaksikan bagaimana jabatan publik menjadi pintu gerbang untuk memperkaya diri dan keluarga. Maka tak heran jika keputusan-keputusan seperti begal pulau ini bisa dengan mudah diambil, walau bertentangan dengan konstitusi dan nurani publik.
Apa yang Harus Dilakukan Rakyat Aceh?
Kasus ini menjadi alarm keras bagi rakyat Aceh dan Indonesia pada umumnya. Jika pembiaran terus terjadi, maka bukan tidak mungkin wilayah-wilayah strategis lainnya akan mengalami hal serupa. Maka yang perlu dilakukan adalah:
- Tekanan Publik Berbasis Data Aksi protes harus didasarkan pada dokumen historis dan hukum yang sah. Publikasi data dan fakta harus dilakukan secara masif agar narasi palsu tidak mendominasi ruang publik.
- Peran Tokoh-Tokoh Lokal dan Nasional Keterlibatan tokoh seperti Jusuf Kalla dan Prof Humam Hamid sangat penting untuk menjaga kredibilitas perjuangan. Ini juga menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar lokal, tetapi menyangkut martabat nasional.
- Desakan Judicial Review Kepmendagri 300.2.2-2138/2025 harus diuji secara hukum di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memastikan konstitusionalitasnya. Mengubah UU dengan Kepmen adalah pelanggaran berat.
- Gerakan Kolektif Masyarakat Sipil Masyarakat sipil Aceh, termasuk mahasiswa, LSM, dan lembaga adat, perlu bersatu menyuarakan aspirasi. Ini bukan sekadar soal pulau, tapi soal identitas dan keadilan.
Ujian Sejarah untuk Pemerintahan dan Rakyat
Aksi begal empat pulau Aceh ini lebih dari sekadar kesalahan administratif. Ia adalah gambaran nyata bagaimana kekuasaan bisa memanipulasi hukum demi kepentingan sempit. Konflik kepentingan yang telanjang ini menjadi cermin betapa bobroknya sistem pengambilan keputusan kita saat ini.
Namun, di balik itu semua, ada harapan. Harapan bahwa rakyat Aceh masih bisa bersatu, berdiri tegak dengan harga diri, dan memperjuangkan haknya dengan cerdas dan terhormat. Sejarah tidak akan lupa. Dan setiap lembar sejarah akan mencatat siapa yang berdiri untuk kebenaran dan siapa yang tunduk demi kekuasaan.
Maka kita, sebagai rakyat, wajib menjaga dan mempertahankan marwah wilayah ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi mendatang. Karena tanah, pulau dan laut yang kita jaga hari ini adalah warisan yang tak ternilai untuk anak cucu kita nanti.
Wallahu a’lam.