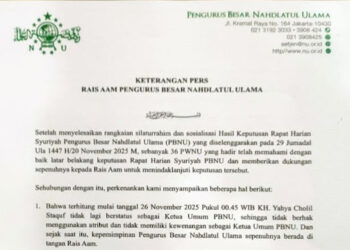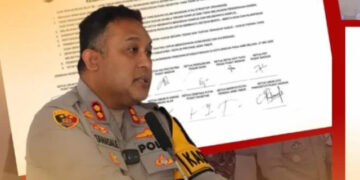BANDA ACEH – Selasa sore, 12 Agustus 2025, suasana di Kantor Flower Aceh tampak berbeda. Kursi-kursi disusun rapat menghadap layar putih di depan ruangan. Bukan untuk pemutaran film atau presentasi proyek pembangunan, melainkan untuk membuka ruang refleksi kritis. Sharing Session #21 – Refleksi 20 Tahun Perdamaian Aceh: Perempuan Ada di Mana?
Mahasiswa magang dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan beberapa program studi lain dari UIN Ar-Raniry bergerak cepat memastikan segala kebutuhan teknis berjalan lancar. Proyektor menyala, menampilkan judul kegiatan besar di layar, sementara catatan-catatan materi telah disiapkan.
Bagi sebagian pihak, dua dekade damai Aceh adalah kisah yang patut dirayakan, tak ada lagi baku tembak, tak ada lagi pos pemeriksaan militer di jalan-jalan utama. Namun, di ruangan itu, narasi yang hadir justru memperlihatkan wajah lain dari perdamaian. Sisi yang jarang terdengar, apalagi masuk ke dalam laporan resmi.
Perempuan yang Hilang dari Narasi Besar
Suraiya Kamaruzzaman, salah satu pendiri Flower Aceh, menjadi pembicara utama sore itu. Duduk tenang di kursi depan, ia membuka sesi dengan suara mantap namun penuh beban cerita. “Sekitar lima ribu pernyataan korban perempuan yang memuat kesaksian tentang empat bentuk kekerasan: penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghilangan paksa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa angka itu bukan sekadar statistik di laporan penelitian. “Ini adalah wajah-wajah yang kita kenal. Tetangga, kawan, saudara. Dan luka mereka belum sembuh.”
Suraiya memaparkan bahwa selama ini perempuan Aceh tidak hanya berposisi sebagai korban. Dalam proses perdamaian, mereka menjadi agen yang memecah kebisuan, melobi dari gampong hingga forum internasional, menggerakkan komunitas akar rumput, mencari nafkah di tengah keterbatasan, bahkan ikut menjadi kombatan. Namun, ketika pembicaraan rekonsiliasi digelar, pengakuan terhadap pengalaman mereka kerap kandas di meja birokrasi dengan alasan teknis: “Mana nomenklaturnya?”
Luka yang Berbeda dari Bencana Alam
Suraiya kemudian menggarisbawahi perbedaan antara korban konflik dan korban bencana alam. Menurutnya, korban bencana mungkin kehilangan rumah atau anggota keluarga, namun korban konflik memikul beban ganda: trauma dan dendam. “Dendam itu bisa diwariskan jika tidak diobati,” ujarnya serius. Hingga hari ini, ia menilai pemerintah belum memberi perhatian yang cukup pada layanan konseling bagi korban konflik, terutama perempuan.
Kondisi ini, menurut Suraiya, berisiko melanggengkan siklus kekerasan dalam bentuk-bentuk baru, bahkan setelah senjata didiamkan.
Tubuh Perempuan Sebagai Arena Tawar-Menawar
Bagian diskusi menjadi semakin hening ketika Suraiya membahas kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik. Ia mengungkapkan bahwa tubuh perempuan kerap dijadikan alat tawar-menawar politik oleh pihak-pihak yang bertikai. Pascadamai, tantangan perempuan tidak berkurang signifikan.
“Patriarki masih kuat, peran domestik masih membatasi ruang gerak, narasi konflik yang maskulin terus mendominasi, dan kita melihat ‘the return of men’. Kembalinya dominasi laki-laki di ruang publik serta kerentanan baru akibat bencana alam,” jelasnya.
Edukasi dan Kesadaran Baru bagi Generasi Muda
Bagi para mahasiswa magang yang ikut terlibat dalam persiapan dan dokumentasi kegiatan, sesi ini menjadi pelajaran lapangan yang berharga. Mereka tidak hanya mempelajari data dan fakta sejarah, tetapi juga memahami kompleksitas dampak konflik terhadap kehidupan sehari-hari.
“Kami belajar bahwa perdamaian bukan hanya soal mengakhiri perang. Ada luka-luka yang tidak pernah masuk berita, ada suara-suara yang tidak pernah diminta bicara,” kata Asma Fitri, salah seorang mahasiswa PMI yang ikut menyimak dari awal hingga akhir.
Moderator kegiatan, Sitty Almatunira, menutup sesi dengan pernyataan tajam: “Kalau pengalaman perempuan terus diabaikan, kita sedang membangun perdamaian yang pincang.”
Membaca Kembali 20 Tahun Damai Aceh
Kegiatan ini menjadi refleksi penting di tengah perayaan dua dekade damai Aceh. Ia mengajak publik untuk melihat bahwa damai tidak boleh didefinisikan hanya sebagai berhentinya tembakan. Damai sejati memerlukan pengakuan, pemulihan, dan keadilan, terutama bagi mereka yang suaranya terpinggirkan dalam narasi besar.
Diskusi ini juga mengungkap bahwa hingga kini belum ada upaya menyeluruh untuk mendokumentasikan secara resmi pengalaman perempuan dalam konflik Aceh, apalagi menjadikannya acuan kebijakan publik. Padahal, pengalaman itu mencakup berbagai peran: dari negosiator, mediator, penggerak ekonomi, hingga pengatur strategi di medan konflik.
Dari Ruang Diskusi ke Perubahan Nyata
Flower Aceh berharap sesi ini menjadi pemicu lahirnya inisiatif baru yang lebih inklusif dalam membangun perdamaian. Dengan menghadirkan mahasiswa lintas disiplin ilmu, diskusi ini memberi ruang untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pemikiran generasi muda yang kelak akan menjadi pembuat kebijakan, peneliti, dan aktivis.
Proyektor yang sederhana, kursi-kursi yang saling berdekatan, dan ruangan yang penuh dengan tatapan serius membuktikan bahwa pengetahuan tidak selalu lahir di aula megah. Ia bisa lahir dari percakapan yang jujur, dari keberanian untuk mengungkap yang selama ini disembunyikan.
Saat peserta mulai meninggalkan ruangan, suasana tetap hening. Tidak ada sorak-sorai atau tepuk tangan panjang. Yang ada adalah tatapan merenung dan langkah pelan, seolah masing-masing membawa pulang satu pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah damai yang kita rayakan ini juga damai bagi perempuan?