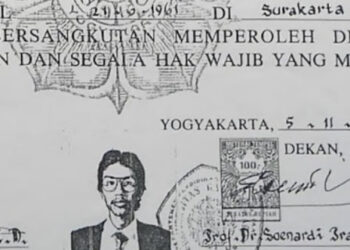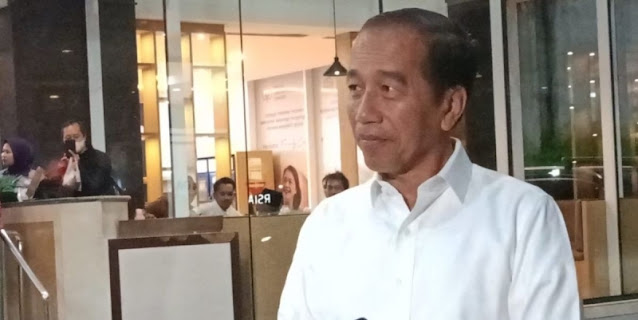Penulis: Maharani dan Sutrisno**
MELONJAKNYA kasus HIV di bumi Aceh yang muncul di laman berita dan media sosial beberapa minggu ini sungguh membuat kita semua terkejut dan tercengang. Ini terjadi karena sebagai praktisi Kesehatan, kami tahu bagaimana virus HIV itu bisa menular dari satu orang ke orang lain.
Aceh kini menghadapi ancaman serius yang jarang disadari oleh banyak orang: peningkatan kasus HIV/AIDS di kalangan usia produktif dan remaja. Data Dinas Kesehatan Aceh, hingga pertengahan tahun 2025 tercatat lebih dari 1200 kasus HIV yang dilaporkan, dengan sebagian besar penderita berusia 20 hingga 39 tahun.
Sebuah ironi yang menyakitkan, mengingat Aceh selama ini dikenal sebagai Serambi Mekkah, wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religiusitas.
Sebagai pendidik dibidang kesehatan reproduksi, kami melihat fenomena ini bukan hanya dari sisi medis, tetapi sebagai darurat sosial dan moral yang harus segera diatasi secara sistematis, bukan sekadar melalui himbauan moral dan retorika lisan.
Program nyata dan praktis harus di ciptakan dan direncanakan agar kasus HIV ini bisa di tekan untuk jangka panjang. Kualitas sumber daya manusia di Aceh menjadi pertaruhan besar bila kasus melonjaknya HIV ini tidak mendapatkan jalan keluar yang tepat.
Mengapa Kasus HIV di Aceh Meningkat?
HIV (Human Immunodeficiency Virus) bukanlah penyakit baru. Namun, selama bertahun-tahun, penyakit ini sering dianggap “jauh dari kita”. Pandangan bahwa HIV hanya menyerang kelompok tertentu misalnya pengguna narkoba suntik atau pekerja seks, membuat masyarakat umum merasa aman. Padahal, kini pola penularan telah berubah: penularan melalui hubungan seksual berisiko tanpa perlindungan justru meningkat pesat.
Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa angka HIV di Aceh terus meningkat. Pertama, kurangnya edukasi dan komunikasi tentang kesehatan reproduksi. Banyak keluarga masih menganggap topik reproduksi dan seksualitas sebagai hal tabu untuk dibicarakan, terutama kepada anak-anak dan remaja. Akibatnya, mereka mencari informasi dari sumber yang salah, termasuk media digital yang tidak terverifikasi.
Kedua, perubahan pola penularan. Jika dulu penularan banyak terjadi melalui penggunaan jarum suntik, kini sebagian besar terjadi melalui hubungan seksual tanpa pelindung, termasuk hubungan sesama jenis yang kini menyumbang lebih dari setengah kasus di Aceh.
Di Aceh, sebagian besar kasus baru ditemukan pada laki-laki usia produktif, dan tidak sedikit pula pada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga menjadi “korban” yang mengenaskan karena mereka umumnya orang yang baik – baik saja, namun karena ulah suaminya / pasangannya, mereka menjadi korban dan cepat atau lambat akan berdampak kepada anaknya.
Sebagai praktisi kesehatan, saya sering menjumpai kasus dimana seorang ibu hamil datang untuk periksa kehamilan dan baru diketahui HIV-positif setelah dilakukan tes laboratorium.
Banyak dari mereka yang menangis karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan, namun ternyata tertular dari pasangan yang terinfeksi terlebih dahulu. Ini adalah tragedi sunyi yang sering luput dari pemberitaan.
Ketiga, stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV. Banyak pasien enggan melakukan pemeriksaan dini karena takut dikucilkan. Mereka baru datang ke fasilitas kesehatan saat kondisinya sudah parah. Ini membuat upaya pencegahan menjadi terlambat.
Keempat, minimnya anggaran dan pemerataan pelayanan. Menurut data Dinas Kesehatan Aceh, dana yang dialokasikan untuk pendampingan petugas HIV di 23 kabupaten/kota hanya sekitar Rp24 juta per tahun. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah dan tingginya kasus.
Kesehatan Reproduksi yang Terancam
HIV/AIDS bukan hanya menyerang daya tahan tubuh, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap kesehatan reproduksi.
Pada perempuan, virus ini dapat menyebabkan gangguan menstruasi, penurunan kesuburan, hingga risiko penularan dari ibu ke bayi saat hamil atau menyusui.
Pada laki-laki, HIV dapat menurunkan kualitas sperma dan menimbulkan disfungsi seksual.
Yang lebih mengkhawatirkan, infeksi HIV di usia produktif mengancam keberlanjutan generasi muda. Usia 20–39 tahun adalah masa di mana seseorang seharusnya berada pada puncak produktivitas, baik dalam pekerjaan maupun peran sosial.
Ketika kelompok usia ini terpapar HIV, dampaknya bukan hanya bagi kesehatan individu, tetapi juga bagi ekonomi keluarga dan terhadap daya saing generasi Aceh di masa depan.
Mengapa Fenomena Ini Terjadi di Aceh?
Banyak yang bertanya, mengapa di wilayah yang dikenal religius seperti Aceh, kasus HIV justru meningkat? Pertanyaan ini sangat relevan.
Namun, jawaban tidak sesederhana menyalahkan moralitas individu. Nilai-nilai moral tidak otomatis menjamin masyarakat bebas dari penyakit, jika edukasi kesehatan tidak berjalan efektif.
Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi yang terbuka dan ilmiah di sekolah maupun masyarakat menyebabkan banyak orang muda tidak memahami bagaimana HIV menular dan bagaimana cara mencegahnya. Kata “seks” masih dianggap tabu untuk dibicarakan, padahal justru di balik ketabuan itu, ketidaktahuan tumbuh subur.
Kedua, mobilitas dan urbanisasi juga berperan besar. Banyak pemuda yang merantau ke luar daerah atau bekerja jauh dari keluarga, lalu kembali ke kampung halaman membawa risiko penyakit menular seksual tanpa disadari.
Ketiga, stigma terhadap penderita HIV masih sangat kuat. Banyak pasien yang enggan memeriksakan diri karena takut dikucilkan. Akibatnya, mereka baru mencari pertolongan saat kondisi sudah parah.
Sebagai praktisi kesehatan, saya sering menemui dilema: di satu sisi ingin melindungi privasi pasien, di sisi lain khawatir akan penularan pada pasangan dan bayi yang dikandung.
Situasi seperti ini membutuhkan empati, pemahaman, dan sistem dukungan sosial yang kuat, bukan penghakiman.
Tantangan Praktis di Lapangan
Dalam praktik lapangan, ada tiga hal yang paling sering menjadi tantangan yakni Pertama, Minimnya deteksi dini, tidak semua puskesmas rutin melakukan skrining HIV bagi ibu hamil, padahal ini penting untuk mencegah penularan ke bayi.
Kedua, kurangnya tenaga kesehatan terlatih, tidak semua tenaga kesehatan mendapat pelatihan memadai untuk konseling HIV, terutama di daerah terpencil sehingga sulit memberikan edukasi tanpa stigma.
Ketiga, kendala sosial dan budaya, pasien sering menolak untuk dites karena takut dianggap “tidak bermoral” oleh lingkungan sekitar.
Padahal, setiap tenaga kesehatan tahu bahwa HIV bisa menimpa siapa saja. Virus ini tidak mengenal latar belakang sosial, agama, atau pendidikan.
Pembicaraan tentang hubungan seksual masih dianggap tabu, bahkan di ruang edukasi formal. Padahal, keterbukaan justru kunci pencegahan.
Saya pernah mendampingi seorang ibu muda yang baru mengetahui status HIV-positif saat hamil anak keduanya.
Ia menangis, bukan karena takut mati, tetapi karena khawatir menularkan bayinya. Kasus seperti ini menggambarkan pentingnya deteksi dini dan komunikasi yang empatik antara tenaga kesehatan dan pasien.
Solusi Bersama: Dari Pemerintah hingga Keluarga
Fenomena HIV di Aceh harus disikapi dengan serius dan menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan kampanye moral, tetapi juga langkah sistematis dan ilmiah.
Pertama, peran Pemerintah harus meningkatkan anggaran dan pemerataan layanan kesehatan reproduksi.
Program Voluntary Counseling and Testing (VCT) perlu diperluas hingga ke sekolah menengah dan pesantren. Edukasi HIV harus diintegrasikan dengan program kesehatan reproduksi dan remaja.
Kedua, peran tenaga kesehatan bidan, dokter, dan perawat harus dilatih untuk memberikan konseling tanpa stigma. Skrining HIV pada ibu hamil harus menjadi bagian rutin dari pelayanan antenatal.
Ketiga, peran keluarga, orang tua harus mulai membuka ruang dialog tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi kepada anak, sesuai usia dan nilai agama.
Menghindari pembicaraan bukan solusi, justru memperbesar risiko ketidaktahuan. Keempat, Peran Masyarakat, perlu mengubah cara pandang terhadap penderita HIV. Mereka bukan pelaku dosa yang pantas dikucilkan, melainkan manusia yang membutuhkan dukungan medis dan sosial.
Refleksi Spiritual
Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehidupan sebagai amanah yang suci. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 32:
“Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”
Ayat ini menegaskan bahwa menyelamatkan satu nyawa dari penyakit, termasuk HIV, adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab kemanusiaan.
Maka, upaya pencegahan, edukasi, dan empati terhadap penderita bukan sekadar kewajiban profesi, tetapi juga panggilan spiritual.
Saatnya Bangkit Bersama
Kasus HIV di Aceh adalah cermin bahwa kita perlu lebih jujur menghadapi realitas, masih ada ruang-ruang sunyi di mana generasi muda terjebak dalam ketidaktahuan dan stigma.
Saat ini, generasi muda sedang menghadapi ancaman yang tidak terlihat, namun nyata menghancurkan masa depan.
Kita tidak perlu malu membicarakan kesehatan reproduksi, sebab diam justru memupuk kebodohan dan bahaya.
Saatnya pemerintah, akademisi, keluarga, dan masyarakat bersatu melindungi generasi produktif dari ancaman HIV.
Karena menjaga mereka bukan hanya soal kesehatan, tetapi soal masa depan Aceh yang lebih bermartabat dan berkeadaban.
**). Penulis:
- Dr. Maharani, S.ST, M.Keb, Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh
- Dr.dr. Sutrisno, Sp.OG, Subsp.FER, Dosen Magister Kebidanan/ Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, Malang