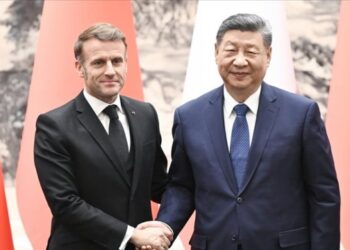Gelombang lumpur maha dahsyat menggulung Sumatera kurun 25-29 November 2025 kemarin. Badai banjir disertai jutaan kubik kayu gelondongan yang turun dari gunung menerjang pemukiman dan kampung-kampung rakyat yang ada di bawahnya. Air bah dan rombongan kayu yang datang tidak pernah dibayangkan sebelumnya seperti itu oleh manusia. Bahkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menyebut peristiwa tragis tersebut sebagai tsunami kedua.
Di Aceh, badai lumpur dan kayu telah menenggelamkan ratusan desa di 18 kabupaten/kota terdampak. Kehancuran sangat parah dialami oleh masyarakat di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara hingga Bener Meriah, Gayo Lues dan sebagian Pidie Jaya tepatnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua.
Hingga hari ini, kehancuran secara kuantitatif ditunjukkan oleh data statistik yang dirilis oleh pemerintah. Namun kehancuran secara kualitiatif, ini tidak terperikan. Korban berteriak hingga mengibarkan bendera putih sebagai isyarat panggilan bantuan cepat, tepat, dan bermartabat dari Negara.
Alhasil, bencana akhir November ini pun menyisakan luka begitu dalam, dan menciptakan traumatik yang sulit dilupakan begitu saja. Ketika itu, logika dan perasaan rakyat Aceh seakan kembali ke masa tatkala menghadapi masa-masa perang, konflik bersenjata, atau kelukaan yang tiada tara. Sangat sulit!
Pembaca! Meski rasa sakit itu belum usai, luka belum kering dan bantuan pemulihan masih dibutuhkan, nun jauh di sana, di Jakarta, Presiden RI Prabowo justru mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan menyatakan ia berharap Tanah Papua turut ditanami sawit, agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit. Padahal banjir bandang besar Aceh-Sumatera diduga terkait erat dengan deforestasi ‘sawit’.
Pertanyaan nya“Mengapa Indonesia Sangat Agresif Mencapai Target Sawit?”
Pembaca! Indonesia bukan sekadar negara produsen sawit terbesar di dunia. Ia telah menjadikan sawit sebagai poros utama pembangunan ekonomi, energi, bahkan politik. Target demi target sawit dicanangkan secara agresif, seolah perluasan kebun adalah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan. Pertanyaannya, mengapa negara begitu ngotot mengejar sawit, bahkan ketika hutan terus menyusut dan bencana ekologis berulang?
Jawaban paling sederhana adalah ekonomi. Sawit menyumbang devisa besar, menciptakan lapangan kerja, dan menopang neraca perdagangan. Dalam bahasa negara, sawit adalah “penyelamat”. Namun, ketika sebuah komoditas diberi peran terlalu dominan, ia berubah dari alat menjadi penentu arah kebijakan. Sawit tidak lagi sekadar tanaman, melainkan ideologi pembangunan.
Agresivitas ini juga berkaitan erat dengan agenda kedaulatan energi. Program biodiesel—B35 hingga B40—menjadikan sawit sebagai tulang punggung transisi energi. Negara ingin lepas dari ketergantungan impor solar dan fluktuasi harga minyak global. Sawit lalu dipoles sebagai energi hijau, ramah lingkungan, dan nasionalis. Namun narasi ini sering mengabaikan fakta bahwa bahan baku biodiesel tersebut berasal dari pembukaan lahan besar-besaran yang justru mempercepat deforestasi dan krisis iklim.
Di balik alasan ekonomi dan energi, terdapat faktor yang lebih sunyi tapi menentukan: kepentingan politik dan oligarki. Industri sawit dikuasai oleh segelintir korporasi besar dengan relasi kuat ke pusat kekuasaan. Dalam banyak kasus, kebijakan negara tampak lebih sigap melindungi kepentingan industri dibanding hak masyarakat adat, petani kecil, atau ekosistem. Konflik agraria, kriminalisasi warga, dan ketimpangan penguasaan lahan menjadi harga yang dianggap wajar.
Tekanan internasional, khususnya dari Uni Eropa, justru memperkeras sikap negara. Alih-alih melakukan koreksi serius terhadap tata kelola sawit, pemerintah sering membingkai kritik lingkungan sebagai serangan terhadap kedaulatan nasional. Sawit dijadikan simbol perlawanan terhadap Barat. Padahal, di dalam negeri, rakyatlah yang pertama kali merasakan dampak dari kebijakan ekspansif tersebut: banjir, longsor, kekeringan, dan hilangnya ruang hidup.
Agresivitas sawit juga mencerminkan watak pembangunan Indonesia yang masih sangat ekstraktif. Hutan dipandang sebagai cadangan ekonomi, bukan sebagai sistem penyangga kehidupan. Selama pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan tunggal, maka pembukaan lahan akan selalu menemukan pembenarannya. Biaya ekologis tidak pernah benar-benar dihitung dalam neraca negara. Banjir dianggap bencana alam, bukan konsekuensi kebijakan.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi mengapa Indonesia agresif mengejar sawit, melainkan sampai kapan model ini dipertahankan. Ketika keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara kerugian ditanggung bersama oleh rakyat dan generasi mendatang, maka agresivitas itu layak digugat. Negara seharusnya berani meninjau ulang arah pembangunan, menempatkan keberlanjutan dan keadilan ekologis sebagai fondasi, bukan sekadar slogan.
Sawit memang bukan musuh, tetapi cara negara memperlakukannya bisa menjadi ancaman. Jika hutan terus dikorbankan demi target produksi, maka yang sesungguhnya sedang dikejar bukan kesejahteraan, melainkan ilusi pertumbuhan. Dan seperti semua ilusi, ia akan runtuh—meninggalkan banjir, lumpur, dan pertanyaan yang terlambat dijawab. []