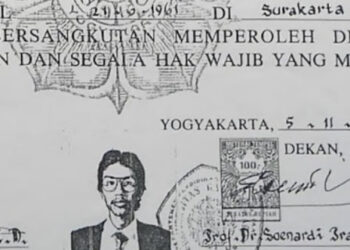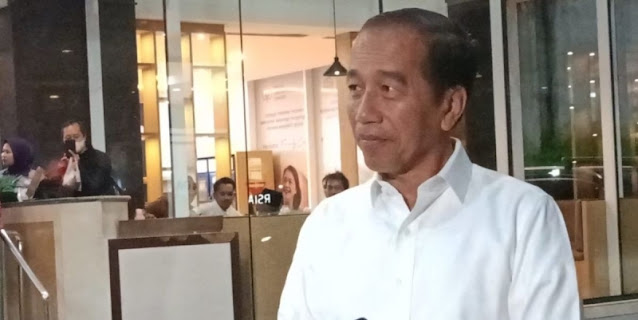Oleh: dr. Masry, Sp. An**
ACEH pernah menjadi panggung dunia. Tsunami 2004 menjadikannya laboratorium kemanusiaan, tempat bangsa-bangsa belajar bagaimana bangkit dari puing. Dua dekade kemudian, panggung itu runtuh di hadapan banjir dan longsor. Ironi yang pahit: dari role model penanganan bencana, kini Aceh menjadi contoh kegagalan mitigasi.
Alarm yang Jadi Arsip
BMKG menyalakan alarm sejak 30 September 2025. Mendagri menegaskan instruksi siaga pada 7 Oktober. Surat resmi BMKG pun mendarat di meja Gubernur pada 20 Oktober. Namun di Aceh, alarm itu lebih mirip arsip: tersimpan rapi, dibuka kembali sebulan kemudian.
Rakyat Berlari, Pemerintah Duduk Rapat
Ketika hujan deras mengguyur pada 24 Oktober, masyarakat pesisir sudah berlari menyelamatkan diri. Pemerintah? Baru duduk rapat pada 24 November. Plt. Kadinsos menenangkan publik dengan kalimat: “Alhamdulillah, buffer stock kita cukup.” Cukup, katanya. Tapi waktu sudah habis.
Koordinasi Lemah, Janji Manis
Rapat itu ditutup dengan janji manis: pentingnya sinergi antarinstansi, konsolidasi data akurat, kesiapan jalur distribusi. Kata-kata indah, tapi banjir tidak menunggu konsolidasi. Bantuan perdana baru turun lewat Kak Na pada 25 November, sehari kemudian.
Pusdokpal yang Tak Berjalan
Pusat Dokumentasi dan Pelaporan (Pusdokpal) yang seharusnya menjadi otak koordinasi, nyaris tak terdengar. Data tercecer, laporan lambat, distribusi tersendat. Aceh kehilangan fungsi vital yang dulu membuatnya dipuji dunia.
Retorika “Tanpa Jeda”
Barulah pada 29 November, Gubernur Aceh bersuara lantang: “Penanganan banjir dan longsor harus dilakukan dengan cepat, terukur, dan tanpa jeda.” Ironi pun lengkap. Setelah jeda 31–34 hari, lahirlah retorika “tanpa jeda.”
Tuntutan Nasional
Kegagalan mitigasi lokal akhirnya memunculkan desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah. Karena itu, mereka mendesak Presiden menetapkan status darurat bencana nasional.
Desakan ini bukan sekadar formalitas. Ia adalah pengakuan bahwa sistem mitigasi daerah telah runtuh. Bahwa koordinasi lemah, logistik terbatas, dan distribusi tersendat bukan lagi masalah teknis, melainkan kegagalan struktural.
Pelajaran Pahit
Aceh yang dulu menjadi teladan kini terjebak dalam birokrasi lamban. Pemerintah tidak tanggap, koordinasi lemah, Pusdokpal lumpuh. Kata-kata lebih cepat dari aksi, hujan lebih sigap daripada birokrasi. Dan kini, masyarakat sipil harus mengetuk pintu Presiden untuk menyelamatkan Aceh dari banjir.
Apa hikmah yang bisa diambil?
Mitigasi bencana Aceh runtuh bukan karena alam, melainkan karena jeda panjang yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Ironi terbesar: dari role model dunia, Aceh kini menjadi alasan tuntutan darurat nasional.
Aceh tidak runtuh karena banjir. Aceh runtuh karena birokrasi yang tenggelam dalam arsip.
Dan di negeri yang pernah menjadi guru dunia, kini rakyatnya harus belajar satu hal pahit: hujan selalu lebih sigap daripada pemerintah.
**). Penulis adalah warga Aceh yang berdomilisi di ujung sudut kota Banda Aceh