Sering kali, ketika musibah datang menimpa kita — banjir, kehilangan harta, ketidakpastian hidup — hati terasa sempit. Kita merasa beban ini paling berat, luka ini paling dalam. Namun, jika kita menengok sedikit ke luar diri, ke luar kampung dan negeri, kita akan sadar: kita bukan yang paling menderita.
Di Aceh, banjir bandang datang tanpa permisi. Air membawa lumpur, kayu, dan puing, merobohkan rumah-rumah sederhana, memisahkan keluarga, dan memutus penghidupan. Ada yang kehilangan sawah, ada yang kehilangan ternak, bahkan ada yang kehilangan orang tercinta. Luka ini nyata, air mata ini sungguh.
Namun pada saat yang sama, di Gaza, saudara-saudara kita hidup di bawah dentuman bom dan reruntuhan. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan rasa aman, kehilangan sekolah bagi anak-anaknya, kehilangan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Bagi mereka, malam bukan lagi waktu istirahat, melainkan waktu menunggu: apakah masih ada esok hari.
Di Sudan, konflik berkepanjangan memaksa jutaan orang mengungsi. Kelaparan dan penyakit mengintai di kamp-kamp darurat. Anak-anak tumbuh tanpa kepastian, para ibu bertahan dengan sisa-sisa harapan. Sementara dunia sering lupa, penderitaan mereka terus berjalan.
Dan Rohingya — yang terusir dari tanah kelahirannya, hidup tanpa kewarganegaraan, tanpa perlindungan hukum. Bertahun-tahun menjadi pengungsi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sering kali ditolak dan dicurigai. Mereka hidup dengan satu pertanyaan pahit: di mana rumah kami?
Mereka semua adalah saudara kita sebagai Muslim dan sebagai sesama orang beriman, bahkan sebagai sesama manusia. Rasulullah Saw mengajarkan bahwa orang-orang beriman itu ibarat satu tubuh; ketika satu bagian sakit, bagian lain ikut merasakan. Maka, musibah yang menimpa Aceh tidak terpisah dari Gaza, Sudan, atau Rohingya. Rasa pedih mereka seharusnya menggugah empati kita, bukan untuk membandingkan derita, tetapi untuk meluaskan hati.
Menyadari bahwa kita bukan yang paling menderita bukanlah untuk mengecilkan luka kita sendiri. Bukan pula untuk melarang kita bersedih. Tapi agar duka itu tidak berubah menjadi keputusasaan, dan agar keluhan tidak mematikan rasa syukur. Dari kesadaran ini, lahir kekuatan: untuk saling membantu, untuk berbagi, untuk mendoakan, dan untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah lalai melihat hamba-Nya.
Barangkali kita masih punya atap meski bocor, sementara yang lain tak punya rumah sama sekali. Barangkali kita masih bisa mengeluh, sementara yang lain bahkan tak punya ruang untuk bersuara. Maka, dari sini, mari kita bangkit bersama: menguatkan yang lemah, mendoakan yang terluka, dan menolong sebisanya. Karena iman bukan hanya soal bertahan dalam ujian, tetapi juga soal hadir bagi sesama yang sedang diuji. ***










































































































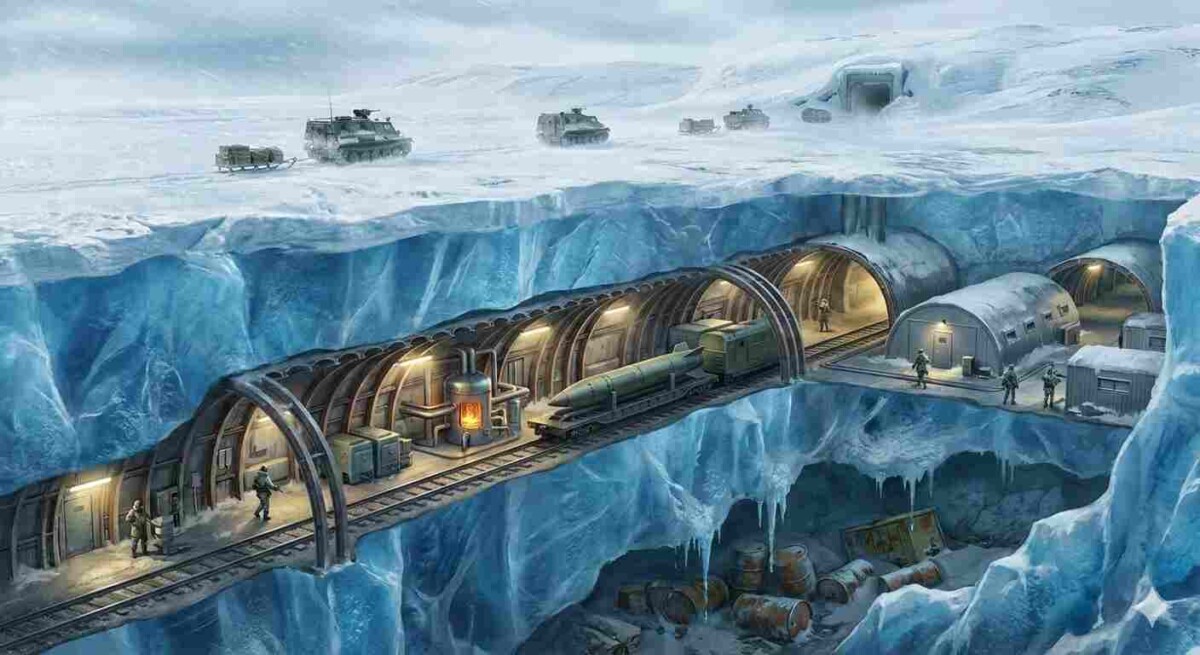






























































Paling Banyak Dipilih
Viral Lagu “Tak Diberi Tulang…
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Inilah 5 Produk Jam Tangan…
Apa benar, yang nomor 4 itu adalah produk ROLEX...???
Berusia Setengah Abad sejak 6/8/1973…
Berikut untuk mengingatkan kita kembali tentang Sejarah: "Kita bukan pembuat…
Pembiayaan Digantung Tak Ada Kabar…
Kriet mate bank Aceh nyan menyoe meurusan ngen ureng Aceh.…
Ada Dua Nama Calon Direktur…
Siapapun nanti dirut yg terpilih, saya siap membantu bas menggarap…
Active Threads
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Hana jelas, Leh kiban di meubut di kelola,Meu peu cap…
Paling Dikomentari
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan…
Rosan Roeslani Bongkar Akal-akalan Keuangan…
Apa itu Rehabilitasi dan Tujuannya
Kabar Gembira, Bustami Hamzah Resmi…
Bukan Sekadar Pelengkap! PTS Kini…
Komentator Paling Aktif
Komentar Paling Aktif
Jeffrey Epstein yahudi nggak jelas dan pelaku pelecehan sensual.
Syukur lah karena seharusnya memang langsung dimakan karena bukan namanya…
Ara lagi salah minum obat. Kami maklum. hahahaha...
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Berita Terpopuler