Di titik ini, bukan rakyat yang terlalu berani menilai, melainkan sistem yang terlalu cepat memvonis penilaian rakyat sebagai kesalahan.
Kita sedang berbicara tentang institusi berseragam, berpangkat, berwenang, dan dibiayai negara. Institusi yang memiliki arsip, database, dan akses biometrik. Namun ironisnya, dalam perkara dua foto wajah, ketelitiannya kerap kalah dari seorang warga biasa yang memperbesar gambar dengan dua jari sambil menyeruput kopi.
Masalahnya bukan ketiadaan alat. Aparat jelas punya alat. Masalahnya lebih mendasar dan lebih kultural: budaya mengejar kepastian administratif, bukan budaya menguji kebenaran visual secara ilmiah. Dalam logika semacam ini, yang dicari bukan jawaban jujur apakah dua foto itu benar-benar menunjukkan orang yang sama, melainkan apakah kesimpulan itu sudah cukup “aman” untuk dipertahankan.
Di sinilah keraguan justru dianggap gangguan. Padahal, dalam ilmu identifikasi wajah, keraguan adalah pintu kehati-hatian. Tanpa keraguan, analisis berubah menjadi pembenaran. Foto tidak lagi dibaca, tetapi diarahkan untuk mengangguk.
Begitu narasi awal ditetapkan -“ini orangnya sama”- foto kehilangan haknya untuk berbicara. Ujung hidung yang berbeda disebut pengaruh usia. Alis yang karakternya bertolak belakang disebut efek cahaya. Bibir yang strukturnya tidak sama disebut pengaruh senyum. Telinga yang jelas-jelas berbeda? Dianggap tidak relevan.
Semua perbedaan dikecilkan. Semua kemiripan dibesarkan. Anatomi dipaksa tunduk pada skenario cerita.
Ironisnya, profil samping, yang dalam kajian forensik justru dikenal penuh jebakan, sering dijadikan dasar keyakinan. Siluet wajah diperlakukan seolah identitas. Padahal siluet itu seperti bayangan sore hari: panjang, dramatis, tetapi miskin presisi. Dua orang berbeda bisa tampak satu, sementara satu orang bisa tampak seperti tiga versi berbeda tergantung cahaya dan sudut kamera.
Di ruang publik, kesalahan semacam ini mungkin hanya berujung perdebatan. Namun ketika ia dibawa ke ranah hukum, akibatnya berubah skala: perbedaan penilaian visual bisa diperlakukan sebagai pelanggaran, bukan sebagai bagian wajar dari nalar manusia.
Yang lebih mengkhawatirkan, baik warga maupun aparat hidup dalam ekosistem yang tidak memberi insentif pada kalimat sederhana, “Belum cukup bukti.” Di media sosial, kalimat itu tidak viral. Dalam praktik birokrasi hukum, kalimat itu dianggap memperlambat proses. Maka jalan tercepat dan terasa paling aman adalah menyederhanakan: nyatakan sama, lalu persoalkan mereka yang berani berkata beda.











































































































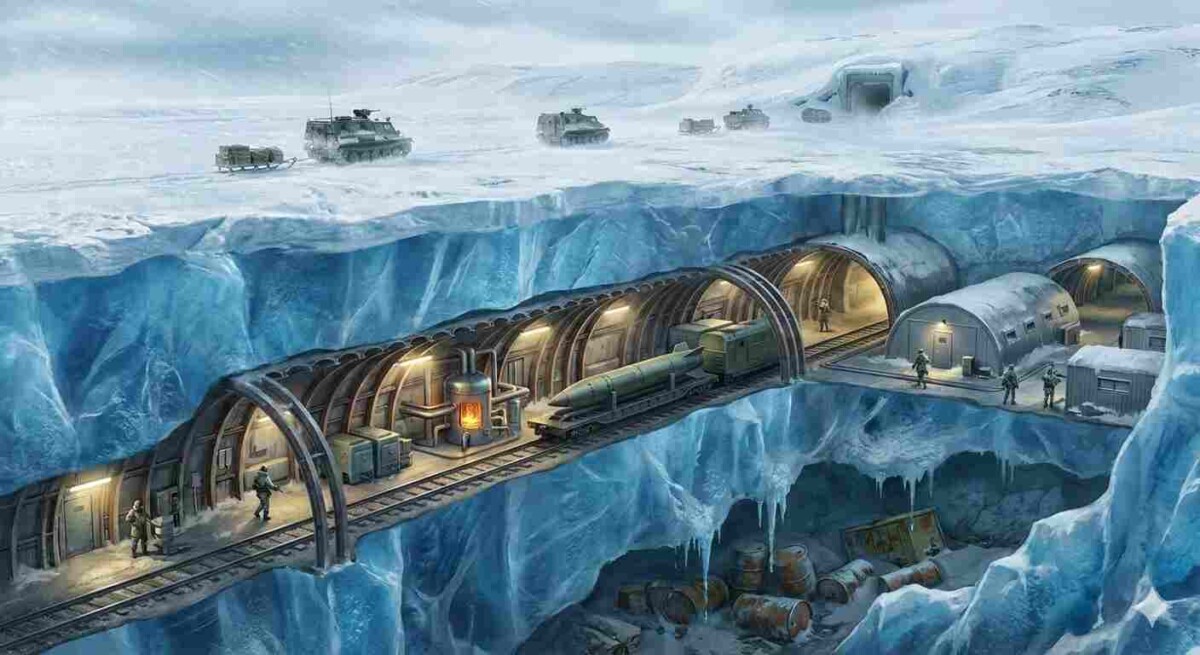





























































Paling Banyak Dipilih
Viral Lagu “Tak Diberi Tulang…
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Inilah 5 Produk Jam Tangan…
Apa benar, yang nomor 4 itu adalah produk ROLEX...???
Berusia Setengah Abad sejak 6/8/1973…
Berikut untuk mengingatkan kita kembali tentang Sejarah: "Kita bukan pembuat…
Pembiayaan Digantung Tak Ada Kabar…
Kriet mate bank Aceh nyan menyoe meurusan ngen ureng Aceh.…
Ada Dua Nama Calon Direktur…
Siapapun nanti dirut yg terpilih, saya siap membantu bas menggarap…
Active Threads
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Hana jelas, Leh kiban di meubut di kelola,Meu peu cap…
Paling Dikomentari
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan…
Rosan Roeslani Bongkar Akal-akalan Keuangan…
Apa itu Rehabilitasi dan Tujuannya
Kabar Gembira, Bustami Hamzah Resmi…
Bukan Sekadar Pelengkap! PTS Kini…
Komentator Paling Aktif
Komentar Paling Aktif
Jeffrey Epstein yahudi nggak jelas dan pelaku pelecehan sensual.
Syukur lah karena seharusnya memang langsung dimakan karena bukan namanya…
Ara lagi salah minum obat. Kami maklum. hahahaha...
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Berita Terpopuler