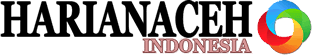BANDA ACEH – Indonesia hari ini kian terasa gelap — bukan semata akibat krisis global atau dinamika geopolitik, melainkan karena redupnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola negara.
Kegelapan ini lahir dari kekuasaan yang semakin tertutup, sentralistik, dan antikritik, sementara akses publik terhadap informasi strategis — dari kekayaan alam hingga kebijakan fiskal — dibatasi secara sistemik.
Dalam sektor kehutanan dan perkebunan sawit, misalnya, publik berhadapan dengan tembok data yang sulit ditembus. Hingga kini, informasi mengenai kepemilikan konsesi, luasan izin, serta keterkaitan korporasi dengan elite politik tidak sepenuhnya terbuka. Padahal, dalam dua dekade terakhir Indonesia telah kehilangan jutaan hektare hutan alam.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan deforestasi kumulatif sejak awal reformasi mencapai angka yang mengkhawatirkan, dengan ekspansi sawit dan tambang sebagai faktor dominan. Ketika data dikuasai segelintir pihak, pengawasan publik melemah, dan kebijakan pun berjalan tanpa koreksi berarti.
Kegelapan serupa tampak dalam pengelolaan utang negara dan anggaran publik. Rasio utang terhadap PDB memang sering ditampilkan dalam batas “aman”, namun transparansi berhenti pada angka makro. Pertanyaan krusial — ke mana utang dialirkan dan siapa yang paling diuntungkan — jarang dijawab secara jujur.
Belanja negara lebih banyak terserap pada proyek-proyek besar dan insentif bagi pemodal, sementara anggaran untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan penguatan layanan dasar kerap tidak tepat sasaran. Akibatnya, utang bertambah, tetapi kesejahteraan rakyat miskin bergerak lambat.
Pada saat yang sama, jarak antara pejabat publik dan rakyat jelata semakin menganga. Sensitivitas sosial memudar, digantikan bahasa kekuasaan yang dingin dan elitis. Kebijakan disusun dari balik meja, jauh dari pengalaman hidup masyarakat terdampak.
Hukum pun tak lagi berdiri sebagai panglima, melainkan kerap dibengkokkan demi kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum menjadi selektif — tajam ke bawah, tumpul ke atas — menciptakan rasa keadilan yang timpang dan kepercayaan publik yang terus tergerus.
Lebih jauh, ruang demokrasi mengalami penyempitan yang mengkhawatirkan. Kritik dianggap ancaman, partisipasi publik direduksi menjadi prosedur elektoral, dan kebijakan strategis diputuskan oleh lingkaran elite yang sempit.
Dalam konteks ini, politik bersekutu erat dengan oligarki ekonomi — para pemilik modal yang memiliki kepentingan langsung atas pengelolaan sumber daya alam. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat koreksi justru dipelintir untuk melanggengkan kekuasaan dan akumulasi keuntungan.
Kondisi di Sumatera hari ini memperlihatkan wajah paling telanjang dari kegelapan tersebut. Banjir besar yang melanda berbagai wilayah bukan sekadar peristiwa alam, melainkan konsekuensi politik dari rusaknya hutan dan tata kelola lahan. Alih fungsi kawasan lindung, pembiaran pembukaan hutan, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan telah menghancurkan daya dukung alam.
Negara gagal hadir sebagai pelindung rakyat dan lingkungan, sementara korban terus berjatuhan di berbagai wilayah Indonesia setiap musim hujan.
Ironisnya, jargon “pembangunan berkelanjutan” dan “perlindungan lingkungan” terus digaungkan di forum internasional. Namun di dalam negeri, jargon itu sering berubah menjadi kosmetik kebijakan — alat pencitraan bagi penguasa dan penghibur bagi publik yang dibodohi oleh narasi resmi. Lingkungan dijaga dalam pidato, tetapi dikorbankan dalam praktik.
Indonesia menjadi gelap ketika negara tidak lagi berpihak kepada rakyatnya. Gelap ketika data disembunyikan, alam dieksploitasi tanpa batas, hukum dibegal, dan demokrasi dirampas perlahan atas nama stabilitas dan pembangunan. Kegelapan ini bukan takdir, melainkan hasil dari pilihan-pilihan politik yang sadar dan berulang.
Maka, menutup akhir tahun 2025, barangkali kita patut memberi selamat pada diri sendiri: Indonesia kembali berhasil menutup tahun dengan konsisten. Konsisten menjaga kegelapan tetap stabil. Transparansi secukupnya, keadilan seperlunya, dan keberpihakan sebatas slogan. Di tengah banjir, kemiskinan, dan kerusakan ekologis, negara tetap tenang — karena yang paling penting bukanlah terang bagi rakyat, melainkan nyaman bagi kekuasaan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia sedang gelap. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: siapa yang diuntungkan oleh kegelapan ini, dan sampai kapan rakyat dibiarkan hidup di dalamnya tanpa cahaya keadilan, transparansi, dan keberpihakan negara?