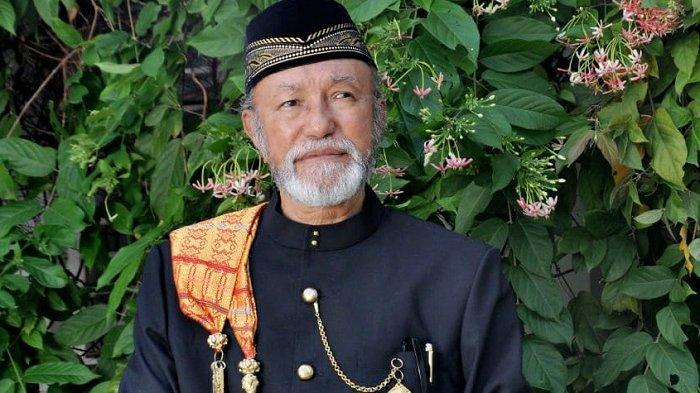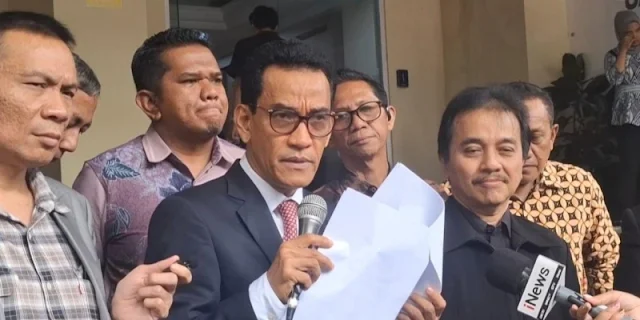Oleh: Dr Chairul Fahmi MA1
PARA pejabat Aceh hari ini sedang mempertontonkan sebuah ironi yang menyesakkan dada. Di saat rakyat di pesisir Timur-Utara masih berjibaku dengan lumpur sisa banjir bandang yang tak kunjung surut, dan ribuan warga di pelosok pegunungan harus menelan pil pahit sebagai daerah termiskin di Sumatera, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 justru hadir tanpa empati.
Dari total plafon Rp12 triliun, sebanyak Rp8 triliun atau sekitar 66 persen habis tersedot hanya untuk belanja pegawai.
Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah lonceng kematian bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebuah potret birokrasi yang lebih sibuk mengenyangkan diri sendiri daripada melayani tuannya: rakyat Aceh.
Ketimpangan ekstrem ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah terjebak dalam “obesitas birokrasi” yang kronis.
Dengan sisa anggaran yang hanya sepertiga untuk membiayai seluruh napas pembangunan di 23 kabupaten/kota, ruang gerak untuk belanja modal menjadi sangat kerdil.
Padahal, secara teoritis, belanja modal adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan menstimulus sektor swasta. Ketika triliunan rupiah habis hanya untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional kantor, maka jangan heran jika jembatan antar desa tetap putus, irigasi sawah mengering, dan rumah sakit kekurangan obat-obatan dasar.
Pemerintah Aceh seolah-olah bertransformasi menjadi sebuah yayasan penyalur gaji raksasa, bukan sebuah entitas politik yang memiliki visi transformatif untuk membawa rakyat keluar dari kubangan kemiskinan.
Kondisi ini semakin menyayat hati ketika kita menengok nasib para korban banjir yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemulihan yang memadai.
Jeritan warga yang kehilangan harta benda dan lahan pertanian seolah membentur dinding tebal gedung-gedung pemerintahan yang megah.
Absennya kehadiran negara di saat krisis bencana menunjukkan adanya disorientasi prioritas yang fatal. Kemiskinan di Aceh yang terus merangkak naik bukanlah takdir atau kutukan geografi, melainkan murni akibat “salah urus” (mismanagement) yang sistemik.
Dana Otonomi Khusus yang seharusnya menjadi katalisator kesejahteraan justru menguap dalam skema belanja rutin yang tidak produktif, meninggalkan rakyat dalam siklus kemiskinan yang kian akut karena tidak adanya intervensi modal dan infrastruktur dari pemerintah.
Kekacauan anggaran ini diperparah oleh praktik “kongkalikong” dana aspirasi yang telah menjadi rahasia umum dalam jagat politik Serambi Mekkah.
Alokasi dana yang seharusnya bersifat strategis untuk kepentingan publik seringkali dipreteli menjadi proyek-proyek kecil “penyenang konstituen” demi kepentingan elektoral oknum politisi.
Di sinilah letak lumpuhnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Alih-alih menjadi anjing penjaga (watchdog) bagi uang rakyat, lembaga legislatif ini justru kerap terjebak dalam hubungan simbiosis mutualisme dengan eksekutif melalui bagi-bagi jatah proyek.
Pengawasan menjadi tumpul karena adanya kepentingan yang searah: bagaimana mengamankan porsi anggaran masing-masing tanpa peduli pada efektivitas dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan.
Secara analisis mendalam, fenomena APBA 2026 ini mencerminkan kegagalan fundamental dalam fungsi alokasi dan distribusi kekayaan daerah.
Aceh sedang mengalami krisis integritas tata kelola di mana anggaran tidak lagi disusun berbasis kebutuhan riil (needs-based), melainkan berbasis kepentingan (interest-based).
Tanpa adanya reformasi radikal untuk memangkas belanja rutin dan mengalihkan fokus pada belanja modal yang padat karya, Aceh akan terus terjebak dalam paradoks daerah kaya anggaran namun miskin rakyatnya.
Jika pola ini terus berlanjut, sejarah akan mencatat bahwa kegagalan Aceh bukan karena kekurangan dana, melainkan karena kegagalan para pemimpinnya dalam memanusiakan rakyat melalui kebijakan anggaran yang berkeadilan.
Struktur APBA 2026 sebesar Rp12 triliun yang mengalokasikan Rp8 triliun untuk belanja pegawai merupakan manifestasi nyata dari patologi birokrasi kronis yang sedang melumpuhkan Aceh.
Secara kritis, angka 66% untuk belanja rutin ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah kehilangan nalar publiknya, birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai pelayan masyarakat (civil servant), melainkan telah bertransformasi menjadi beban parasit bagi struktur fiskal daerah.
Fenomena ini mencerminkan apa yang dalam teori administrasi publik disebut sebagai Parkinson’s Law, di mana birokrasi cenderung memperluas diri dan menyerap anggaran demi eksistensi internalnya sendiri tanpa korelasi positif terhadap output kesejahteraan.
Di tengah jeritan kemiskinan yang menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera, keberpihakan anggaran yang begitu timpang ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dana Otonomi Khusus yang seharusnya menjadi akselerator pembangunan, bukan sekadar instrumen pembiayaan gaya hidup aparatur.
Analisis mendalam terhadap ketimpangan ini mengungkap adanya ritualisme anggaran yang mematikan empati sosial.
Ketika belanja modal dan pembangunan ditekan hingga titik nadir, Pemerintah Aceh secara sadar sedang melakukan pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur dan stagnasi ekonomi.
Dampaknya sangat nyata: korban banjir di pesisir Timur-Utara dibiarkan bertarung dengan nasib tanpa skema rehabilitasi yang mumpuni, sementara mesin birokrasi di Banda Aceh terus melaju dengan tunjangan yang stabil. Ketidakmampuan anggaran untuk menyentuh akar persoalan kemiskinan ini bukan sekadar masalah teknis akuntansi, melainkan kegagalan moral kepemimpinan.
Strategi pembangunan yang “obese” di sisi belanja pegawai namun “anoreksi” di sisi belanja modal memastikan bahwa kemiskinan di Aceh akan terus diproduksi secara sistemik karena ketiadaan intervensi produktif pada sektor riil dan pemberdayaan masyarakat bawah.
Lebih jauh lagi, patologi ini diperparah oleh simbiosis mutualisme yang koruptif antara eksekutif dan legislatif melalui mekanisme dana aspirasi.
DPRA, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam mengawasi penggunaan uang rakyat, justru terjebak dalam pola regulatory capture—di mana pengawas “dijinakkan” melalui bagi-bagi jatah proyek dalam alokasi aspirasi.
Praktik kongkalikong ini menciptakan lubang hitam dalam akuntabilitas publik; anggaran tidak lagi disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan rakyat (needs-based), melainkan berdasarkan negosiasi politik di ruang gelap (interest-based).
Akibatnya, pengawasan menjadi tumpul dan fungsi checks and balances lumpuh total. Lemahnya kontrol parlemen ini memberi ruang bagi eksekutif untuk terus mempertahankan struktur anggaran yang tidak sehat, menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang tertutup, elitis, dan tidak responsif terhadap krisis kemanusiaan maupun ekonomi yang sedang mendera rakyat Aceh.
Pada akhirnya, struktur APBA 2026 adalah sebuah bom waktu fiskal bagi masa depan Aceh pasca-berakhirnya dana Otonomi Khusus.
Dengan ketergantungan yang luar biasa pada dana transfer pusat dan keengganan untuk melakukan reformasi birokrasi yang radikal, Aceh sedang menuju kebangkrutan fungsi pelayanan publik.
Tanpa adanya keberanian untuk memangkas belanja pegawai yang tidak produktif dan menghentikan praktik dana aspirasi yang manipulatif, Aceh akan terus terjebak dalam paradoks kemiskinan: sebuah daerah dengan anggaran triliunan rupiah yang habis hanya untuk memberi makan birokrasinya sendiri.
Sementara rakyatnya tetap merana di bawah garis kemiskinan dan ketidakpastian bencana.***
Catatan Kaki:- Penulis adalah Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry[↩]